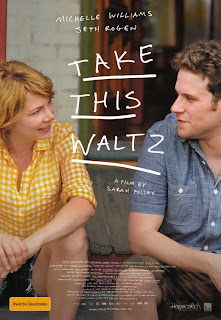Director: John Madden
Cast: Judi Dench, Tom Wilkinson, Bill Nighy, Maggie Smith, Dev Patel, Ronald Pickup
Rate: 4/5
Terkadang, ada beberapa film yang dibuat bukan untuk diikutsertakan dalam ajang-ajang spektakuler sedunia. Bisa jadi film itu hanya sebagai dedikasi atau ada maksud lain yang ingin disampaikan sutradaranya. Begitulah kesan yang saya liat selama menonton The Best Exotic Marigold Hotel (TBEMH) ini. Tidak ada art direction yang apik, tokoh-tokoh dengan tubuh langsing dan tampang rupawan, tidak ada juga lagu-lagu memorable sepanjang film. TBEMH dipersembahkan memang dengan jiwa filmis yang menggetarkan hati penonton jika cinta adalah objek universal yang bisa dirasakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. John Madden, yang dulu pernah memberikan Judi Dench peran hitungan menit yang memukau dan menghantarkannya mendapatkan patung Oscar, sekali lagi mengajak Dench di proyek sederhananya ini.
Ada Evelyn, seorang janda yang akan meneruskan bisnis suaminya, Graham yang merasa peran pentingnya di pemerintahan tidak diperhatikan lagi, Muriel yang tidak kerasan dengan kehidupan sekitarnya, Tuan dan Nyonya Ainslie yang diambang perceraian dan miskin rasa harmonis, Norman dan Madge yang sama-sama masih mencari kepuasan cinta di usia renta mereka. Secara kebetulan yang menyenangkan, ketujuh tokoh ini memilih kota Jaipur, India, untuk tujuan masing-masing mereka. Awalnya yang tidak saling kenal, pertemuan mereka di bandara, serta perjalanan panjang menuju Hotel Marigold, menjadi bumbu yang paling sedap dari film ini. Kocak. Sialnya, Hotel Marigold yang terbayang di benak mereka sangat berbeda dari aslinya.
Kita memang tidak akan melihat pelataran yang memanjakan mata. Sejauh mata memandang, Jaipur adalah kota kecil di India yang terkesan sempit dan kumuh. Yah, seperti kebanyakan kota di India lainnya. Bahkan 'best' dan 'exotic' yang terbaca di judulnya sama sekali tidak ada realisasinya di setting hotelnya sendiri. Tapi jangan salah, film ini menyimpan harta karun yang melimpah. Ketujuh tokoh kita yang terbiasa dengan kebiasaan di Inggris, di sini merasa ketakutan dengan produk Asia beserta hingar-bingar dan hiruk pikuk kota Jaipur ini. Some can adapt solemnly, some feel bad-adaptation. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana masing-masing tokoh bisa memahami posisi mereka di tempat asing. Dan bagaimana nasib Hotel ini sendiri, biarlah terjawab oleh tiap penonton.
Cinta di usia senja. Satu-satunya pokok yang dibicarakan TBEMH. Semua teka-teki terpecahkan dan sebagai penonton yang budiman, pendiktean klasik seperti ini memang menyenangkan. Apalagi hal ini bisa dijadikan sedikit moral lesson bagi kita. Luar biasanya lagi, ada sedikit twist yang bisa jadi tidak akan terbaca oleh kita sedari awal. Dialog-dialog yang keluar dari mulut tokohnyapun begitu segar dan menyentuh. Celetukan sinis dari Muriel, quote-quote bermutu dari Evelyn, petikan-petikan kalimat cinta dari Sonny, sindiran dari Graham, dan sentilan-sentilan ringan arti cinta dari sisa tokohnya. Scriptwriter film ini adalah sang juara. Memadukan kisah biasa namun unik ini di tengah tandusnya India dengan bantuan aktor-aktor mumpuninya. Yah! Dench, Smith, Wilkinson, Nighy, dan lainnya dengan cekatan dan tanpa cela sukses menginterpretasikan karakter mereka dengan sempurna. Bakat adalah bakat, dan bakat tanpa pengalaman adalah hampa. Pengalaman mereka di dunia peran memang membuktikan mereka jika pekerjaan mereka di film ini sangat jelas membantu jalannya film menjadi lebih bermakna.
Ending film ini menuntaskan banyak hal yang tertunda. Dan tereksekusi dengan sangat manis dan rapih. Sesekali saya tertawa dan tersenyum melihat tabiat mereka dan dengan tidak sengaja malah menceritakan masa lalu mereka sendiri. Inilah harta karun yang seperti saya katakan di awal review. TBEMH dengan sangat berhasil sebagai film drama memikat, dengan isi jompo namun kualitas masa kini. Sesederhana itu memang arti cinta, namun kadang terasa rumit jika kita tidak ingin sejalan dengan rasa cinta itu sendiri. Terdengar basi bukan? Happy watching!
by: Aditya Saputra